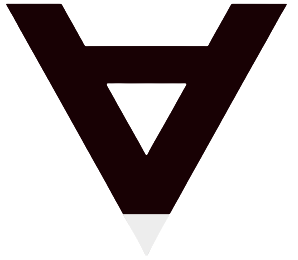Indonesia dan Politik Ketokohan

Akhir-akhir ini, politik adalah topik yang paling hangat dibicarakan. Menjelang pilpres, hampir semua sosial media isinya adalah konten terkait politik. Scrolling twitter sebentar, isinya adalah buzzer-buzzer dari berbagai kubu, membahas beragam isu terkait pilpres. Scrolling tiktok juga tidak berbeda. Ada banyak sekali video singkat terkait politik, membahas kelebihan dan kekurangan masing-masing tokoh politik. Tren ini bahkan menjangkau masuk lebih dalam, obrolan-obrolan gue bersama teman-teman terdekat pun udah masuk ke ranah politik. All aspect in my life now filled by politics.
Akhir-akhir ini, politik adalah topik yang paling hangat dibicarakan. Menjelang pilpres, hampir semua sosial media isinya adalah konten terkait politik. Scrolling twitter sebentar, isinya adalah buzzer-buzzer dari berbagai kubu, membahas beragam isu terkait pilpres. Scrolling tiktok juga tidak berbeda. Ada banyak sekali video singkat terkait politik, membahas kelebihan dan kekurangan masing-masing tokoh politik. Tren ini bahkan menjangkau masuk lebih dalam, obrolan-obrolan gue bersama teman-teman terdekat pun udah masuk ke ranah politik. All aspect in my life now filled by politics.
Sebenarnya, it’s a good trend. Buat gue, keputusan para elitik dibahas di mulut-mulut masyarakat adalah tanda bahwa masyarakat tidak buta politik. Program kerja, rekam jejak dan gagasan yang dicuitkan di sosial media merupakan bukti bahwa rakyat sudah semakin sadar, bahwa keputusan politiklah yang akan banyak mempengaruhi mereka: harga pangan, pendidikan, hingga penyelesaian ketimpangan. Kelebihan dan kekurangan masing-masing calon yang diperbincangkan akan membuat kita bisa menentukan, kemana arah Indonesia (setidaknya) lima tahun kedepan. For me, this moment should be a good moment.
Namun, menelisik lebih dalam, that’s not what happen. Perbincangan yang terjadi bukan membandingkan mana yang terbaik, tapi justru saling adu tokoh pilihan siapa yang lebih heroik. Melihat sosial media, akun-akun yang ada tidak membandingkan apa yang ditawarkan tiap individu, namun malah justru fanatik buta membentuk kubu. Saling serang, saling menjelekkan pilihan lawan menjadi lumrah terjadi, tanpa sadar bahwa pilihan sendiri juga bukan titisan nabi. Even worse, demi membela tokoh yang diagungkan, informasi-berita hasil rekayasa dan opini-opini cacat logika pun dipertontonkan, tanpa dicek kefaktualannya. Sangat disayangkan, Indonesia (masih) terjebak politik ketokohan.
Indonesia dan Politik Ketokohan
Ditengah era reformasi, politik di Indonesia masih mengandalkan sosok kefiguran seseorang untuk mendongkrak suara, daripada memanfaatkan ideologi atau kebijakan tertentu. Elektabilitas suatu partai, suara yang diperoleh masing-masing calon penguasa sangat bergantung pada tokoh mana yang lebih digandrungi masyarakat. Fenomena ketokohan ini makin terasa pada saat pemilu, dimana rakyat yang memilih mendasarkan pilihannya pada persona tiap calon yang dipoles. Semakin kuat citra sang tokoh yang dibentuk, maka semakin banyak orang mengidolakan sang tokoh, maka semakin besar peluang sang tokoh terpilih.
Fenomena ini jelas dimanfaatkan oleh elit politik di negeri ini. Tokoh yang menjadi calon bukan merupakan pemangku kebijakan terbaik, atau calon dengan kompetensi dan pengalaman yang panjang, tapi tokoh dengan citra kefiguran yang kuat. Pada pemilu kali ini misalnya, pilihan yang ada merupakan hasil rembuk tokoh mana yang punya citra paling kuat, antara Anies si intelektual yang religius, Prabowo si berwibawa nan gemoy, atau Ganjar si ramah dan merakyat. Pemilihan calon wakil presiden juga punya nasib serupa. Pemilihan Cak Imin misalnya, diharapkan mampu menjadi tokoh pembawa suara di Jawa Timur, melengkapi Anies yang kuat di Jawa bagian barat. Pemilihan Gibran sebagai wakil Prabowo bisa diharapkan membawa elektabilitas sang ayah, Jokowi, di berbagai daerah. Pemilihan Mahfud pun tak lepas dari sosok ketokohannya yang punya image baik dan tegas di masyarakat.
Dengan tokoh yang punya citra yang kuat, diharapkan tingkat keterpilihan calon dari masing-masing parpol pun meningkat. Banyak partai politik sekarang kuat karena punya tokoh yang kuat. PDIP berjaya karena punya sosok Megawati. Gerindra berjaya karena punya sosok Prabowo. Demokrat yang sempat berjaya karena sosok SBY. Karenanya, coattail effect dari masing-masing tokoh dimanfaatkan, mulai dari pemasangan foto sang tokoh di alat peraga kampanye masing-masing calon legislatif, branding partai sebagai partai-nya salah satu tokoh, hingga praktek dinasti, pencalonan keluarga sang tokoh demi elektabilitas yang mumpuni. Banyak tokoh artis yang sudah punya citra yang mumpuni pun terjun ke dalam kontestasi.
Sebenarnya, politik ketokohan sebenarnya bukanlah suatu hal yang negatif. Ideologi dan tokoh memang seringkali tak bisa dipisahkan. Lama sebelum masa reformasi, ideologi-ideologi yang ada justru banyak didorong oleh ketokohan. Ideologi “marhaenisme” yang sekarang dibawa oleh PDIP misalnya, tak lepas dari sosok ketokohan Soekarno kala itu. Sosok ketokohan Mohammad Natsir juga mampu membawa ideologi keislaman yang dituangkannya kedalam partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) menjadi salah satu partai terbesar, yang sekarang diteruskan oleh Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dua ideologi besar yang ada saat ini justru dibawa oleh ketokohan seorang figur pada masanya.
Namun, praktek politik ketokohan akan membuat kita semua lebih mementingkan citra apa yang tampak daripada program apa yang ditawarkan. Figur mana yang lebih terlihat menarik, figur mana yang terlihat lebih pro rakyat, figur mana yang lebih menyenangkan hati sang pemilih-lah yang akan difokuskan oleh masyarakat, tanpa menilik kembali apa ideologi, apa gagasan, apa program yang ditawarkan. Pada titik tertentu, orang bisa saja tidak melihat kembali apa yang dibawa oleh tiap politisi, tapi hanya melihat citra yang terbentuk dimedia. Asal citra sang tokoh menyenangkan hati sang pemilih, tokoh tersebutlah yang akan maju tanpa dikulik apa yang akan dia lakukan nanti.
Lebih berbahaya, karena citra bertujuan memenangkan hati, maka fanatisme-lah yang justru terjadi. Pendewaan sang tokoh berujung fanatik buta, pengerahan segala macam cara diupayakan agar sang tokoh terlihat istimewa. Sang tokoh dipuja sedemikian rupa, hingga lupa kekurangan yang dipunya bukannya dievaluasi, malah ditutup-tutupi. Berita bohong, opini cacat logika dikerahkan agar ego pribadi terpenuhi, tanpa sadar hal itu hanya justru menguntungkan pribadi sang politisi. Saling serang, saling menjatuhkan pun terjadi demi sang pilihan yang belum tentu memikirkan pemilih punya kepentingan. Parahnya, pendapat yang terpolarisasi malah justru menyebabkan friksi. Bukannya membentuk arah yang mempersatukan, malah justru mendorong adanya perpecahan. Bukannya menjadi mensejahterakan, malah justru memakan pengorbanan.
Mungkin, kita semua perlu diingatkan, citra dapat dipoles. Dengan kekuatan media, banyak individu yang aslinya buruk mampu dipoles menjadi apapun yang masyarakat dambakan. Dulu, pihak penjajah kolonial mampu memoles seorang Snouck Hurgronje yang merupakan seorang utusan Belanda yang beragama Protestan taat, menjadi seorang Abdul Gafar, tokoh ulama Muslim yang diikuti oleh banyak masyarakat di Aceh. Dengan ketokohannya, beliaulah yang memberi informasi kepada Belanda tentang bagaimana menaklukan Aceh, Atceh Verslag. Ironis, bagaimana tokoh yang dielu-elu malah justru yang menjadi penghambat untuk bersatu.
Politik adalah soal kepentingan
Banyak yang bilang, politik adalah soal kepentingan. Banyak yang bilang, dalam politik tak ada kubu yang abadi, semua hanyalah berdasar kepentingan pribadi. Mungkin, seharusnya kearah situlah politik kita bertransformasi. Pilihlah tokoh mana yang punya pemikiran yang paling beneficial dengan kita. Bandingkan program siapa yang paling sesuai dengan semua urusan kita. Cari sosok mana yang membawa gagasan yang bisa menguntungkan kita. One man one vote, buatlah suara kita menjadi suara yang menguntungkan kepentingan kita.
Udah sih gitu aja, bye!